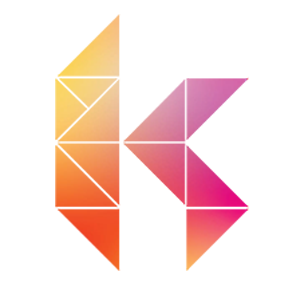Pejabat Pembuat Konten: Antara Pelayanan dan Pencitraan
DALAM beberapa tahun terakhir, fenomena pejabat publik yang gemar membuat konten makin marak.

DALAM beberapa tahun terakhir, fenomena pejabat publik yang gemar membuat konten makin marak.
Mulai dari TikTok hingga YouTube, mereka berlomba-lomba tampil di hadapan kamera. Ada yang menari, membuat vlog kegiatan harian, bahkan dramatisasi sidak atau penyaluran bantuan.
Bagi sebagian orang, itu dianggap sebagai bentuk keterbukaan dan kedekatan pejabat dengan rakyat. Namun benarkah demikian?
Mengutip dari Tempo, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM), membentuk tim khusus yang bertugas mengikuti aktivitas demi memproduksi konten sesuai dengan preferensi.
Melalui kanal YouTube 'Kang Dedi Mulyadi Channel, tim tersebut digerakkan secara intensif untuk membangun citra KDM sebagai figur pemimpin yang dekat dengan rakyat dan layak dirindukan.
Tidak sedikit warganet berkomentar bahwa pejabat publik memiliki mandat utama melayani masyarakat, bukan membangun popularitas pribadi. Sayangnya fenomena 'pejabat konten kreator' justru menimbulkan pertanyaan serius soal prioritas.
Ketika kamera lebih dahulu dinyalakan sebelum bantuan disalurkan. Ketika agenda kerja disesuaikan demi viralitas. Alih-alih efektivitas, maka itu bukan lagi pelayanan. Itu adalah panggung.
Memang benar, konten bisa menjadi alat komunikasi. Akan tetapi, ketika substansi kerja ditutupi oleh kemasan bombastis, masyarakat hanya mendapat tontonan, bukan kepastian pelayanan.
Terlalu banyak energi habis untuk mengelola citra, sementara problem struktural seperti kemiskinan, pendidikan, dan infrastruktur tetap stagnan.
Antara Transparansi dan Pencitraan
Dalih keterbukaan kerap digunakan untuk membenarkan aktivitas konten para pejabat. Akan tetapi, transparansi tidak membutuhkan dramatisasi.
Kejelasan laporan kinerja, indikator capaian terukur, serta kanal aduan yang aktif jauh lebih berarti daripada vlog di kantor atau video makan bersama rakyat.
Apalagi tidak sedikit pejabat menggunakan konten untuk memoles kegagalan. Ketika kritik mengalir, mereka tidak menjawab dengan solusi, melainkan dengan konten baru yang lebih menyentuh sisi emosional publik.
Itu adalah bentuk pencitraan politik berupa memamerkan diri tanpa substansi kebijakan yang nyata. Alhasil, masyarakat sekadar berperan sebagai penonton, bukan subjek.
Lebih buruk lagi, dalam banyak konten, masyarakat kerap dijadikan latar belakang pasif. Mereka direkam, disorot, dan kadang penderitaan mereka dieksploitasi untuk memperkuat narasi kepedulian sang pejabat.
Ironisnya setelah kamera mati, tidak tampak keberlanjutan solusi, sehingga yang tersisa hanya jejak digital dan pujian sementara.
Kembali ke Esensi
Fenomena ini harus dikritisi secara jernih. Publik tidak menolak penggunaan media oleh pejabat, tetapi harus dibedakan antara komunikasi publik dan pencitraan murahan.
Pejabat seharusnya menjadi problem solver, bukan selebritas. Jangan membiarkan fungsi negara direduksi menjadi konten viral. Negara bukan panggung hiburan dan rakyat bukan figuran.
Fenomena pejabat yang hobi membuat konten bukan sekadar soal gaya komunikasi baru, tetapi cermin dari niat politik yang tidak selalu murni.
Ketika seorang pejabat sibuk tampil di media sosial, rakyat patut bertanya, apakah ini benar-benar demi transparansi atau hanya demi elektabilitas?
Publik sekarang juga terlalu sering dijejali potongan-potongan visual yang seolah menunjukkan kerja nyata. Akan tetapi, kerja nyata tidak selalu perlu kamera. Justru ketika setiap tindakan selalu dipoles menjadi konten, muncul sinyal bahwa yang lebih dikejar bukan solusi, tetapi simpati.
Banyak pejabat yang tampaknya tidak ingin dikenal karena keberhasilan membenahi sistem, tetapi karena tampilan yang 'merakyat' dan 'humble' di layar.
Investasi Menuju Pemilu
Mari bersikap jujur! Sebagian besar konten itu bukan dibuat untuk rakyat, tetapi untuk algoritma dan pemilih. Akun media sosial dijadikan investasi jangka panjang menuju pemilihan kepala daerah terdekat.
Video menyalurkan bantuan, menyapa warga, atau berpura-pura kaget dengan harga pasar bukan bentuk empati. Itu adalah kampanye dini terselubung.
Rakyat tidak butuh aktor, tetapi butuh pemimpin. Masyarakat tidak memerlukan pejabat yang piawai berakting. Mereka membutuhkan pemimpin yang bekerja sungguh-sungguh tanpa harus tampil di depan kamera.
Juga pemimpin yang lebih fokus membenahi sistem daripada mengejar popularitas di media sosial demi meraih followers.
Ketika niat membuat konten lebih besar daripada niat membenahi masalah, maka negara telah diseret masuk ke ruang produksi sinetron politik tanpa akhir.
Sudah saatnya publik kritis dan tidak mudah terbuai narasi visual. Pejabat yang baik tidak perlu banyak konten, karena kinerja akan berbicara sendiri.
Masyarakat juga perlu membongkar niat di balik layar, apakah pelayanan tulus atau ambisi kekuasaan yang dibungkus dengan senyum kamera?
Fenomena ini menunjukkan bagaimana politik visual bisa menipu publik kalau tidak disertai verifikasi fakta. Konten yang manis sering kali menutupi realita pahit.
Masyarakat perlu lebih kritis. Jangan hanya menilai pejabat dari unggahan, tetapi dari dampak nyata kebijakan dan kualitas hidup warga.
Pemimpin Dalam Islam
Dalam tradisi kepemimpinan Islam, pejabat bukan figur yang sibuk membangun citra, melainkan sosok penuh amanah, takut hisab, dan menghindari popularitas tidak perlu.
Khalifah Umar bin Khattab, misalnya. Dikenal justru menangis ketika diangkat menjadi pemimpin karena menyadari tanggung jawab di hadapan Allah.
Khalifah Umar terkenal karena kebiasaan berkeliling di malam hari untuk memastikan kebutuhan rakyatnya terpenuhi. Bukan demi mencari pujian, melainkan karena kesadaran dengan tanggung jawab besar di akhirat.
Tidak ditemukan catatan yang menunjukkan bahwa Khalifah Umar gemar memamerkan kepedulian kepada publik. Tidak tercatat panggung megah atau narasi dibuat-buat. Semua yang dilakukan adalah kerja nyata dan diam-diam, dilandasi ketulusan dan rasa takut kepada Allah.
Pemimpin dalam Islam tidak sibuk terlihat baik, tetapi sibuk menjadi baik. Penyebabnya mereka memegang prinsip bahwa penilaian manusia itu fana dan yang kekal adalah pertanggungjawaban di akhirat.
Dalam Islam, menjadi pemimpin berarti menjalani amanah, bukan memburu sorotan. Kalau sekarang masyarakat menyaksikan pejabat yang lebih tertarik membangun persona di media sosial ketimbang membenahi masalah rakyat, maka ini adalah penyimpangan dari nilai-nilai dasar kepemimpinan dalam Islam.
Itu adalah deviasi dari amanah yang menjadikan jabatan sebagai panggung, bukan sebuah pelayanan. Wallahu a’lam bisshawab.
Oleh: Mila Ummu Muthiah
(Aktivis muslimah)